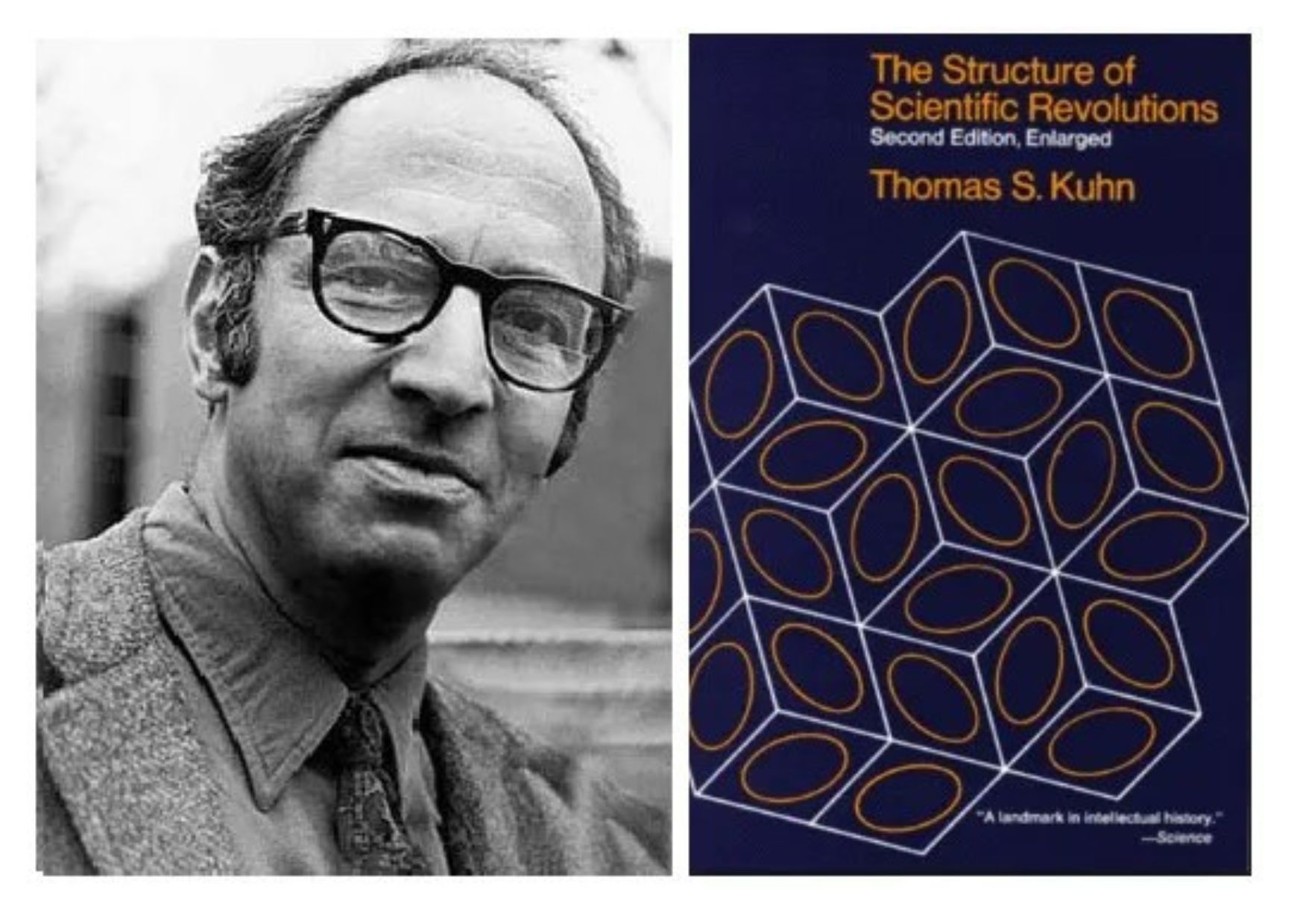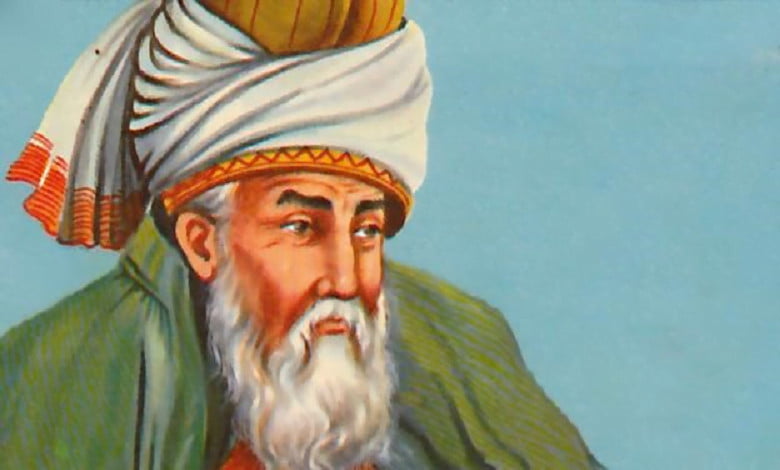Oleh: T.H. Hari Sucahyo*
Thomas Kuhn adalah salah satu filsuf ilmu pengetahuan paling berpengaruh pada abad ke-20 yang mengubah cara kita memahami perkembangan ilmu. Melalui karya monumentalnya The Structure of Scientific Revolutions (1962), Kuhn memperkenalkan gagasan mengenai “paradigma” dan “revolusi ilmiah” yang kemudian menjadi istilah pokok dalam diskursus filsafat sains. Kuhn menolak pandangan linear tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang dianggap sekadar akumulasi fakta.
Baginya, ilmu berkembang melalui fase-fase yang kadang stabil dan normal, lalu diguncang oleh krisis, hingga akhirnya muncul lompatan radikal yang ia sebut revolusi ilmiah. Untuk menjelaskan sifat revolusi ilmiah, Kuhn kerap membuat analogi dengan revolusi politik, karena keduanya sama-sama melibatkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat, baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat politik; memahami, menyusun, dan mengatur dunia mereka.
Kuhn melihat bahwa baik dalam dunia ilmu maupun politik, stabilitas adalah keadaan yang normal. Dalam dunia ilmu, stabilitas itu hadir dalam bentuk “sains normal,” yakni aktivitas penelitian sehari-hari yang dijalankan dalam kerangka paradigma yang telah diterima luas oleh komunitas ilmiah. Paradigma memberi arahan tentang apa yang harus diteliti, metode yang dipakai, bahkan cara menafsirkan hasil.
Dalam dunia politik, stabilitas terwujud dalam bentuk rezim yang mapan dengan aturan main yang diakui oleh warganya, baik berupa undang-undang, konstitusi, maupun norma yang berlaku. Namun, stabilitas ini tidak bersifat abadi. Dalam kedua ranah itu, krisis bisa terjadi ketika anomali atau persoalan-persoalan baru tidak bisa lagi ditangani dengan cara lama. Ilmuwan akan menghadapi fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma dominan, sementara warga atau kelompok politik menghadapi ketidakadilan, ketidakmampuan pemerintahan, atau krisis legitimasi.
Dalam penjelasan Kuhn, anomali dalam sains adalah gejala-gejala empiris atau hasil eksperimen yang tidak sesuai dengan prediksi paradigma yang berlaku. Awalnya, para ilmuwan cenderung menutup mata atau berusaha menyesuaikan hasil tersebut agar tetap bisa dimasukkan ke dalam kerangka paradigma lama. Tetapi jika anomali terus menumpuk dan menjadi semakin signifikan, komunitas ilmiah mulai kehilangan kepercayaan terhadap paradigma yang ada.
Hal ini serupa dengan situasi dalam politik ketika rezim yang berkuasa gagal menjawab masalah-masalah mendesak, sehingga kepercayaan rakyat terhadap legitimasi penguasa kian menurun. Kegagalan dalam mengelola krisis ekonomi, ketidaksetaraan sosial, atau ketidakmampuan mengatasi konflik bisa menjadi “anomali politik” yang memicu delegitimasi. Dalam kedua kasus, krisis itu membuka pintu bagi munculnya alternatif baru, baik berupa paradigma ilmiah baru maupun sistem politik baru.
Revolusi ilmiah, menurut Kuhn, terjadi ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang sama sekali berbeda cara pandang, metode, dan kriteria kebenarannya. Perubahan ini bukanlah sekadar perbaikan atau penyesuaian kecil, melainkan pergeseran radikal yang mengubah wajah seluruh bidang ilmu. Misalnya, revolusi Copernican yang menggantikan pandangan geosentris Ptolemaik dengan pandangan heliosentris; revolusi Newtonian yang menggantikan mekanika Aristotelian; atau revolusi Einsteinian yang mengguncang hukum Newton melalui teori relativitas.
Semua itu bukan sekadar tambahan fakta baru, melainkan perubahan cara mendasar dalam memandang realitas alam. Demikian pula, revolusi politik melibatkan perubahan sistemik yang mendalam, bukan sekadar pergantian elite. Revolusi Perancis 1789, Revolusi Rusia 1917, atau Revolusi Amerika adalah contoh bagaimana sistem politik, sosial, dan hukum lama digantikan oleh tatanan baru dengan dasar-dasar yang sama sekali berbeda.
Salah satu kesamaan menarik yang ditunjukkan Kuhn adalah sifat non-kumulatif dari revolusi. Dalam perkembangan sains normal, pengetahuan bersifat kumulatif: fakta-fakta baru ditambahkan pada kerangka lama tanpa mengubah dasarnya. Tetapi dalam revolusi ilmiah, paradigma baru tidak sekadar menambahkan fakta, melainkan mengubah makna fakta itu sendiri. Fakta yang sebelumnya dianggap “masalah” bisa menjadi sesuatu yang masuk akal dalam kerangka baru.
Misalnya, pergerakan planet yang tidak sesuai dengan prediksi sistem Ptolemaik dianggap anomali, tetapi dalam sistem Copernicus menjadi konsisten. Hal yang sama terjadi dalam revolusi politik: hukum, institusi, bahkan identitas warga bisa berubah makna ketika rezim baru berkuasa. Hak-hak istimewa bangsawan di bawah monarki, misalnya, kehilangan arti ketika republik lahir. Dengan demikian, baik revolusi ilmiah maupun revolusi politik menandai diskontinuitas tajam, lompatan yang memutus kontinuitas sebelumnya.
Kuhn juga menekankan adanya dimensi psikologis dan sosiologis dalam proses revolusi. Dalam dunia ilmu, tidak semua ilmuwan langsung menerima paradigma baru. Sebagian keras kepala bertahan pada paradigma lama, terutama mereka yang telah menghabiskan hidupnya membangun karier di atas fondasi itu. Perdebatan bisa berlangsung sengit, bahkan menimbulkan friksi dalam komunitas ilmiah. Hanya ketika generasi baru ilmuwan tumbuh dan paradigma baru berhasil menunjukkan keunggulannya dalam memecahkan persoalan, barulah paradigma itu mapan.
Pola ini mirip dengan revolusi politik, di mana pergantian rezim jarang berlangsung mulus. Selalu ada pihak yang bertahan, ada konflik, ada tawar-menawar, dan ada transisi yang membutuhkan waktu. Bahkan, dalam kedua jenis revolusi itu, kemenangan paradigma baru atau rezim baru bukanlah hasil dari argumen rasional semata, melainkan juga dari dinamika kekuasaan, persuasi, dan perubahan aliansi sosial.
Analogi Kuhn juga tampak dalam soal legitimasi. Dalam sains normal, paradigma menjadi otoritas yang menentukan mana penelitian yang sahih dan mana yang menyimpang. Paradigma ini memiliki kuasa mengatur standar metodologi, teori, bahkan bahasa ilmiah yang dipakai. Dalam politik, rezim berkuasa berperan sebagai otoritas yang menetapkan hukum, kebijakan, dan aturan main. Tetapi ketika paradigma atau rezim kehilangan legitimasi akibat krisis, muncul ruang bagi perdebatan terbuka tentang alternatif baru.
Momen ini yang memungkinkan terjadinya revolusi. Setelah revolusi, legitimasi baru harus dibangun kembali. Paradigma baru membutuhkan konsensus ilmuwan, sementara rezim politik baru membutuhkan kesepakatan sosial dan pengakuan rakyat. Tanpa legitimasi, paradigma baru tidak bisa menjadi kerangka bagi sains normal, sama seperti rezim baru yang tidak bisa memerintah tanpa dukungan rakyat.
Kuhn juga menekankan perbedaan penting antara revolusi ilmiah dan revolusi politik. Dalam politik, revolusi sering disertai dengan kekerasan fisik, penggulingan paksa, dan perubahan drastis dalam struktur ekonomi maupun sosial. Sementara itu, revolusi ilmiah biasanya berlangsung dalam ranah ide, diskursus, dan praktik ilmiah, meski dampaknya pada kehidupan manusia bisa sama besar atau bahkan lebih luas.
Selain itu, revolusi politik dapat dipicu oleh kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu, sementara revolusi ilmiah cenderung lahir dari ketidakmampuan paradigma lama menjelaskan fenomena alam. Walau demikian, Kuhn menyadari bahwa komunitas ilmiah juga tidak steril dari kepentingan, sehingga faktor sosial, budaya, bahkan ekonomi tetap bisa memengaruhi arah revolusi ilmiah.
Menariknya, dengan membandingkan revolusi ilmiah dan revolusi politik, Kuhn sebenarnya juga sedang mengingatkan bahwa:
“ilmu pengetahuan bukanlah aktivitas yang sepenuhnya objektif atau bebas nilai. Ilmu pengetahuan adalah praktik sosial yang berlangsung dalam komunitas tertentu dengan norma, tradisi, dan otoritasnya sendiri. Sama seperti politik, ia bisa mengalami konflik, krisis legitimasi, dan pergantian “rezim” dalam bentuk paradigma.”
Gagasan ini membuat filsafat sains bergeser jauh dari gambaran klasik yang menekankan objektivitas murni, rasionalitas linier, dan akumulasi fakta. Kuhn menunjukkan bahwa perkembangan ilmu sangat mirip dengan dinamika manusia dalam masyarakat dan politik: penuh tarik-menarik, konflik, krisis, dan lompatan.
Bagi banyak orang, analogi antara revolusi politik dan revolusi ilmiah membuka wawasan baru bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang netral dan steril, melainkan bagian dari dinamika kebudayaan manusia. Ketika paradigma baru hadir, ia tidak hanya mengubah laboratorium dan ruang kuliah, tetapi juga cara masyarakat memahami dunia. Teori heliosentris mengubah pandangan keagamaan dan filsafat manusia tentang posisinya di alam semesta.
Teori relativitas mengguncang konsep ruang dan waktu yang selama ini dianggap pasti. Demikian juga revolusi politik: ia tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga cara warga menafsirkan hak, kewajiban, dan identitas mereka. Dalam kedua ranah ini, revolusi adalah titik balik sejarah yang meninggalkan dampak panjang.
Kesimpulannya, perbandingan antara revolusi politik dan revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn menunjukkan adanya pola serupa dalam dinamika sosial dan dinamika ilmu pengetahuan. Keduanya sama-sama lahir dari krisis yang tak teratasi oleh tatanan lama, sama-sama melibatkan delegitimasi otoritas lama, dan sama-sama menghasilkan lompatan radikal menuju tatanan baru yang berbeda secara mendasar. Keduanya juga sama-sama bersifat non-kumulatif, penuh perdebatan, dan membutuhkan proses legitimasi ulang.
Perbedaannya terletak pada ranah dan instrumen: revolusi politik sering berwujud kekerasan fisik, sedangkan revolusi ilmiah lebih bersifat konseptual, meski keduanya sama-sama bisa mengubah arah sejarah umat manusia. Dengan kerangka ini, Kuhn berhasil menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar pencarian kebenaran objektif, tetapi juga sebuah praktik manusiawi yang tak terpisahkan dari dinamika sosial, psikologis, dan historis. Seperti halnya politik, ilmu pengetahuan pun bergerak melalui periode stabilitas, krisis, revolusi, lalu stabilitas baru yang pada akhirnya juga akan diguncang oleh krisis berikutnya.
__________
* T.H. Hari Sucahyo, merupakan Pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group “Sapientiae”. IG : har1scyhebat