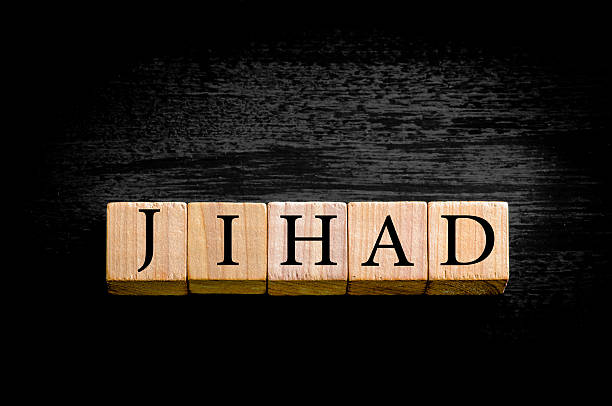Oleh: Nova Dewi Azzahra
Tidarislam.co- Zaman sekarang, kita sering kali mendengar anak-anak muda berbincang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Di ruang kelas, seminar, media sosial, bahkan dalam keseharian, bahasa ini digunakan karena dianggap mampu memberi kesan keren, pintar, dan profesional. Berdasarkan Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin (2023) yang dilakukan oleh Sinaga, dkk., generasi muda lebih cenderung menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam komunikasi sehari-hari. Sementara itu, bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi bahasa pemersatu, perlahan tergeser menjadi sekadar pelengkap.
Penggunaan bahasa asing maupun bahasa gaul semakin merajalela seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini disebabkan oleh hegemoni yang telah menjangkau hampir seluruh aspek penggunaan bahasa Indonesia (Abni, S.R.N. et al., Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025). Berdasarkan jurnal tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa Indonesia hari ini berada dalam posisi yang sulit: digunakan, tetapi tidak lagi dimuliakan. Ia masih hadir dalam ruang-ruang formal seperti sekolah, instansi pemerintahan, dan berita resmi. Namun, di ruang digital yang kini mendominasi kehidupan anak muda, bahasa Indonesia justru terpinggirkan—digantikan oleh bahasa asing yang dianggap lebih keren, gaul, dan bergengsi.
Fenomena ini tak hanya terbatas di media sosial atau lingkungan pergaulan, tetapi juga merambah dunia profesional. Istilah seperti meeting, deadline, jobdesk, upgrade, hingga mindset lebih sering diucapkan dibandingkan padanan bahasa Indonesianya. Padahal, bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang tak kalah kuat dan jelas. Sayangnya, banyak yang menganggap kata-kata asing terdengar lebih modern dan “kelas atas”, sedangkan bahasa Indonesia terasa membosankan, kaku, bahkan “jadul”.
Fenomena ini dalam kajian sosiolinguistik disebut sebagai xenoglosofilia, yaitu ketertarikan berlebihan terhadap bahasa asing bukan karena kebutuhan komunikasi, melainkan sebagai simbol status dan gaya hidup.
Karina D. Rahmawati et al. (2023) menyebut bahwa xenoglosofilia “mengancam eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi, terutama di kalangan generasi muda yang menggunakan bahasa asing secara berlebihan demi prestise sosial.” (Jurnal Penelitian Pendidikan). Inilah mengapa bahasa Inggris kerap digunakan bahkan ketika tidak diperlukan, semata-mata untuk terlihat lebih “kelas atas”, bahkan hanya untuk gengsi.
Bahasa Indonesia pun perlahan kehilangan ruang hidupnya. Ia digunakan karena diwajibkan, bukan karena dicintai. Ia hanya menjadi formalitas untuk mengisi biodata, membuat laporan, atau menjawab soal ujian. Namun untuk menulis caption di Instagram, membuat konten di TikTok, atau bahkan menulis esai di kampus, bahasa asing jauh lebih diminati. Banyak pula konten edukatif berbahasa Inggris yang menyasar penonton lokal, seolah itulah satu-satunya cara untuk tampil pintar dan relevan.
Ini bukan sekadar soal gaya bahasa, tapi soal identitas. Ketika suatu bangsa mulai merasa malu menggunakan bahasanya sendiri, itu pertanda jati diri mereka sedang terguncang. Kita sering lupa bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga cermin cara berpikir, merasa, dan menilai. Bahasa membentuk logika serta memengaruhi kedalaman pemahaman kita terhadap realitas.
Baca juga: BookTok & Literasi: Bagaimana TikTok Mengubah Cara Gen Z di Indonesia Membaca
Negara lain telah membuktikan bahwa globalisasi tidak harus meminggirkan bahasa nasional. Salah satu contoh nyata adalah Korea Selatan. Meskipun kontennya mendunia, mereka tetap menggunakan Hangul sebagai bahasa utama. Keberhasilan ini bukan semata hasil tren budaya pop, tetapi buah dari strategi panjang dan komitmen negara dalam memperkenalkan dan membanggakan bahasanya ke dunia.
Dalam jurnal Korean Language Education in the Era of Globalization, Jonstn (2023) menjelaskan bahwa pemerintah Korea secara aktif membentuk dan memperluas King Sejong Institute, lembaga pengajaran Bahasa Korea di luar negeri. Melalui kurikulum yang terstruktur dan materi ajar yang kontekstual, mereka berhasil menanamkan nilai-nilai budaya sekaligus menjaga martabat bahasa.
Hal serupa juga tampak di Jepang dan Tiongkok yang tetap menjunjung tinggi bahasa nasional dalam berbagai bidang mulai dari industri kreatif, ilmu pengetahuan, hingga teknologi. Mereka mampu berdiri di panggung dunia tanpa kehilangan jati diri. Kita pun memiliki potensi serupa, selama ada komitmen bersama yang dijalankan dengan konsisten.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Solusi dari persoalan ini bukan dengan melarang penggunaan bahasa asing. Justru yang perlu dibangun adalah kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Apakah kita cukup bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang yang kita sukai, bukan hanya saat diwajibkan? Apakah kita bisa menciptakan ruang ekspresi anak muda yang tetap keren tanpa harus berbahasa asing?
Upaya literasi kebahasaan perlu ditanamkan sejak dini mulai dari keluarga, sekolah, hingga media. Bahasa Indonesia harus kembali hidup dalam keseharian generasi muda, bukan hanya hadir di dokumen resmi, tetapi juga dalam film, musik, permainan digital, dan media sosial. Sudah saatnya bahasa Indonesia tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi menjadi identitas yang melekat yang kita cintai, banggakan, dan hidupi setiap hari.
Baca juga: Bahasa, Dakwah, dan Budaya
Referensi
- Abni, S. R. N., Nasution, D. K., & Fitriani, R. (2025). Pengaruh bahasa asing terhadap eksistensi Bahasa Indonesia di kalangan remaja. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 123–130.
- Jonstn, J. (2023). Korean language education in the era of globalization — With the focus on books and teaching materials. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya, 12(2), 85–97.
- Rahmawati, K. D., Haryanti, S., & Nugraheni, F. (2023). Xenoglosofilia: Ancaman terhadap Pergeseran Bahasa Indonesia di Era lobalisasi. Jurnal Penelitian Pendidikan, 23(2), 101–110.